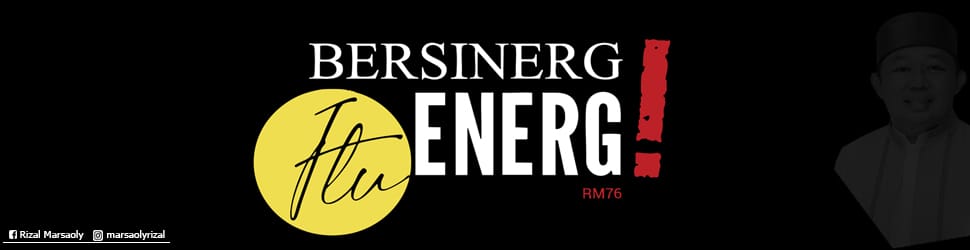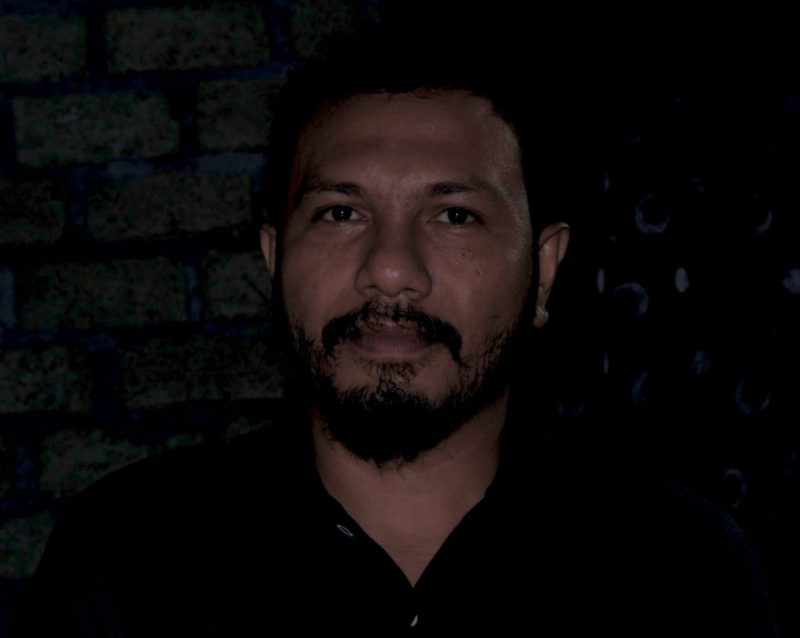Nurkholis Lamaau
(Jurnalis & Pegiat Lingkungan)
Media sosial tiba-tiba ramai dengan potret kerusakan pulau-pulau kecil akibat aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Memang, tidak semua gambar itu asli. Beberapa di antaranya hasil rekayasa dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tapi gambar tersebut kemudian memicu reaksi dari warganet. Tidak sedikit yang membantah keaslian dari gambar itu. Maraknya penyebaran gambar kerusakan pulau di Raja Ampat membuat sejumlah pihak angkat bicara.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Meidy Katrin Lengkey menyebut saat ini sulit membedakan mana yang asli, mana yang manipulasi. Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, gambar viral kerusakan Pulau Piyanemo di Raja Ampat adalah hoaks.
Dalam pendekatan semiotika –ilmu tentang tanda — gambar-gambar tersebut tidak berdiri sendiri. Ada semacam motifasi atau dorongan memproduksi sesuatu untuk diinterpretasikan dalam konteks tertentu. Ia semacam pengingat atas memori manusia yang pendek.
Di sini saya melihat AI bukan sekadar rangkaian teknologi yang menjalankan fungsi penerjemah. Tapi dia semacam mesin yang ikut berpikir bersama kita. AI bisa menghasilkan gambar yang tampak natural dan realistis, meskipun itu hasil rekayasa yang oleh sebagian media ditulis manipulatif.
Sebagai jurnalis yang dituntut disiplin verifikasi, bagi saya, tidak ada tawar-menawar untuk menerima hoaks sebagai sebuah kebenaran. Tapi revolusi industri dari mesin uap hingga era internet kemudian memberi kita dua pilihan: menjadikan AI sebagai tempat pelarian dari kerja-kerja berpikir, atau sebagai mitra intelektual untuk memacu kedalaman berpikir.
Memang, ini sesuatu yang paradoksal. Tapi sikap kita untuk menanggapi kerja-kerja AI–terutama dalam konteks kerusakan lingkungan hidup–jelas tidak sederhana.
Ibarat pedang bermata dua: AI bisa saja melemahkan otak kita yang dituntut aktif dan reflektif. Tapi di sisi lain, AI semacam memiliki kemampuan untuk memberi penyadaran, atau sebagai alarm.
Saat masyarakat Buli di Halmahera Timur ramai-ramai menolak kehadiran perusahaan tambang nikel PT Priven Lestari yang akan menambang di wilayah pegunungan Wato-wato, beredar gambar yang memperlihatkan wilayah perbukitan tampak gundul.
Sementara, di kaki bukit terdapat area pemukiman yang seolah terdiam menanti nasib. Tak lupa diberi tagar #SaveWatowato.
Setelah saya telusuri, gambar itu terinspirasi dari potret Desa Kawasi di Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan, yang di belakangnya terdapat kawasan pertambangan dan industri pengolahan nikel PT Harita Group. Gambar itu mengilustrasikan bagaimana nasib Buli jika Priven Lestari beroperasi.
Sebagai jalan tengah, saya melihat ini bukan tentang menerima kepalsuan sebagai sebuah kebenaran. Tapi bagaimana cara kita melihat secara jernih terhadap apa yang diilustrasikan.
Sebab, mustahil kita menolak teknologi AI yang berwatak dinamis itu. Maka yang kita butuhkan adalah menanamkan refleksi dalam setiap keputusan digital.
Saya menyadari, bahwa karakter dari informasi hoaks adalah selalu menumpang pada peristiwa yang melingkupinya. Distorsi atas sebuah fakta kemudian membangun persepsi setiap orang.
Tapi dalam konteks ekologis, jika potret kerusakan pulau itu hanyalah kerja AI semata, lantas bagaimana cara kita memahaminya secara nyata? Di sini, kognisi memainkan peran penting untuk melihat sisi lain dari rekayasa AI tersebut.
Di Halmahera Timur, misalnya, jika Anda berkendara dari Buli ke Kota Maba, yang tampak di depan mata hanya kerusakan pulau-pulau di sekitar teluk. Ini adalah cerminan ‘kengerian’ yang nyata dari rekayasa AI yang seringkali tak lepas dari sentuhan estetik.
Tugas kita mungkin semakin berat untuk memberikan penyadaran melalui pendekatan apapun. Termasuk lewat AI. Sebab, kebenaran memang menuntut disiplin verifikasi.
Tapi perlu dicatat, bahwa hampir semua praktik-praktik perampasan ruang hidup warga yang sedang berlangsung di daratan Pulau Halmahera, tak mampu divisualkan oleh AI, alih-alih viral.
Padahal, kita baru saja dihebohkan dengan laporan hasil riset Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako, yang menemukan kandungan logam berat berupa arsenik dan merkuri dalam organ ikan hingga aliran darah manusia. Ini adalah puncak dari serangkaian industri ekstraktif yang berlangsung dalam waktu singkat.
Laporan itu ditayangkan di halaman utama harian Kompas, yang saya kira mudah diakses oleh elite-elite di Jakarta. Tapi semua mata kemudian tertuju pada Raja Ampat, dengan menempatkan “pariwisata dunia” sebagai isu utama yang berujung pada pencabutan empat izin usaha pertambangan.
Lalu, bagaimana dengan Halmahera? Jawabannya tidak sederhana.
Sulit menemukan satu kesadaran bahwa perlindungan atas hutan, sungai, laut, dan udara, hingga makhluk hidup menjadi kunci utama. Sebab biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan semua utang-iutang ekologi itu, jauh lebih besar daripada royalti yang diberikan perusahaan kepada negara.
Dengan melihat potret kerusakan pulau yang divisualkan AI, saya meminjam sebuah ungkapan dari Said Marsaoly, warga Buli yang saat ini berjuang mengusir perusahaan tambang nikel PT STS dari tanah Memeli, bahwa; “alam tak hanya ciptaan, tapi cerminan. Apa yang rusak di luar sesungguhnya adalah pantulan yang retak di dalam”.