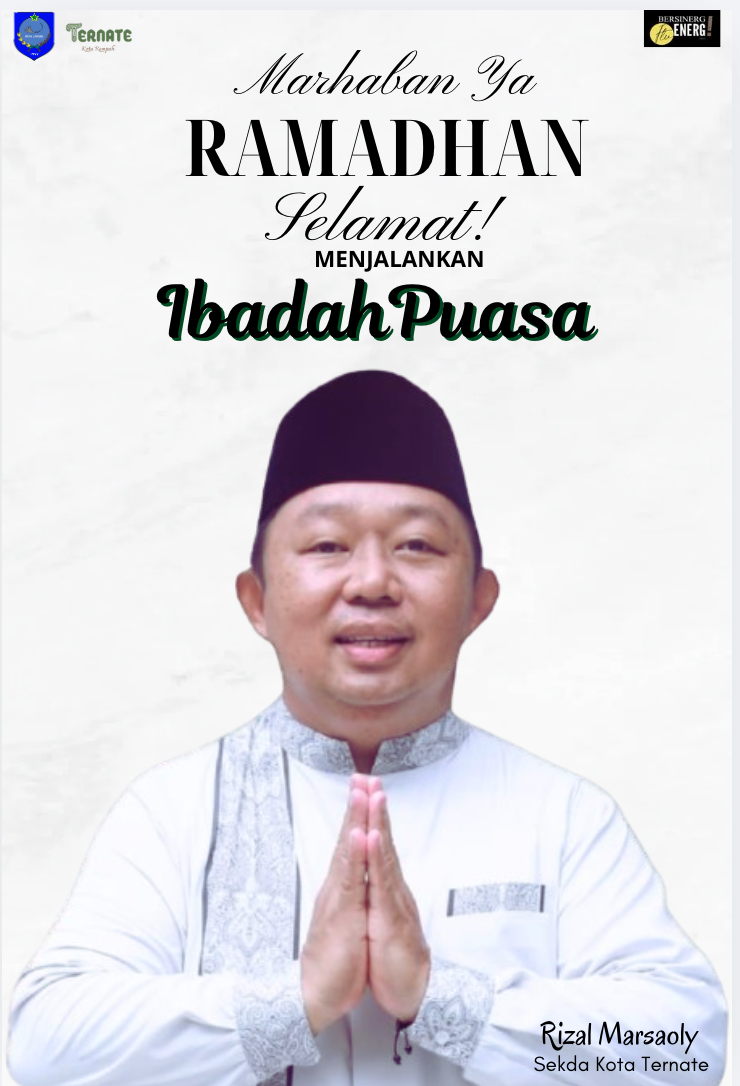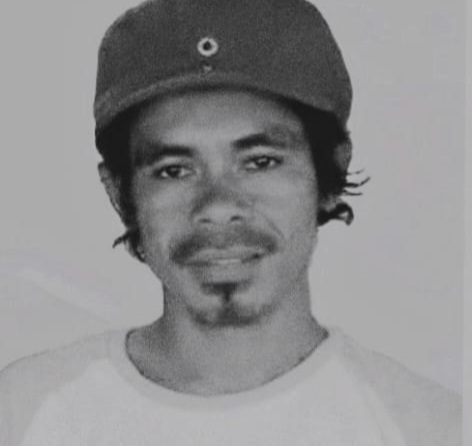Sarfan Tidore
(Owner Commune Coffee)
Bagi orang pesisir, profesi nelayan dan laut menjadi bagian dari hidup mereka. Bila kondisi laut terganggu tentu akan sangat berpengaruh pada kehidupan nelayan. Sebuah selasi (antara nelayan dan laut) yang tidak sekedar alat bergantung hidup—melainkan suatu konstruksi relasi saling menghidupkan yang oleh Bourdieu disebut habitus.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Seorang nelayan asal Tidore Kepulauan, Abdurahman mengatakan, kitorang (kami) ini orang pesisir dan profesi nelayan melekat sejak zaman dahulu kala. Profesi yang diwariskan bukan melalui pendidikan tinggi, bukan pula melalui ceramah di ruang kelas, tetapi melalui praktek sebagai proses pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kepada kami. Dan alat tangkap yang digunakan adalah berupa pancing, soma (jaring) dan panah.
Sekalipun menggunakan alat tangkap sederhana dan pendapatan tidak sebesar nelayan modern yang sekali tangkap hasilnya bisa mencapai ton. Tetapi kami merasa bangga dengan profesi ini. Karena pekerjaan sebagai nelayan setidaknya dapat menghidupi kehidupan kami dari generasi ke generasi. Apalagi laut sudah menjadi bagian dari hidup orang pulau”, ujar Abdurahman.
Suatu pekerjaan tak harus menuntut pendapatan tinggi asalkan dapat penuhi kebutuhan subsisten rumah tangga. Intinya suatu pekerjaan itu perlu dinikmati dan dapat menyatu dengannya. Jika kita tidak menikmati pekerjaan yang kita geluti, maka, yang ada, adalah keluh-kesah dan selalu merasa kekurangan.
Abdurahman berupaya menggali dan menyulam kembali pengalaman melautnya. Saya belajar melaut sejak usia 12 tahun dan kala itu ikut bersama ayahnya mengail (memancing) ikan dasar. Alat tangkap yang digunakan adalah nilon, gumala (kail) dan perahu sampan. Melaut biasanya pada pagi atau sore hari.
Mengapa harus pagi atau sore menjadi waktu yang tepat menangkap ikan? Tanyanya. Sebab pagi dan sore adalah jam dimana ikan mencari makan. Jenis ikan yang ditangkap diantaranya kerapu (goropa), kakap, butila, bubara, ikan gora dan jenis ikan dasar lainnya. Dulu, tahun 1990-an melaut 2-3 jam saja hasilnya cukup banyak.
Sekarang ini bila melaut hasilnya sangat berbeda jauh. Entah kenapa ikan makin berkurang, makin sulit dicari dan bahkan lokasi-lokasi yang dulunya terdapat banyak ikan, namun sekarang mereka sudah berpindah. Pengetahuan tentang lokal untuk mendekteksi lokasi ikan semakin kabur. Kenyataan ini bila dinalar secara holistik bisa dikatakan ada problem mendasar yang tengah terjadi pada kehidupan laut.

Sebab secara fungsional, alat tangkap yang digunakan oleh nelayan tradisional terbukti dapat menjaga, merawat kehidupan laut, tidak merusak ekosistem laut. Berbeda dengan alat tangkap modern yang digunakan seperti perahu mesin berbahan bakar bensin, solar, pukat harimau, pajeko dan mereka menangkap ikan tidak tebang pilih, ikan kecil pun dilibas habis.
Pengunaan alat tangkap modern memiliki risiko tertentu dan berdampak serius pada kehidupan bawa laut. Semisalnya bunyi mesin dapat mengganggu kehidupan ikan. Penggunaan bahan bakar bensin, solar, pembuangan plastik di lautan dapat mencemari air laut. Begitu juga dengan pukat harimau, pajeko dan pengeboman ikan tidak hanya berdampak pada berkurangnya biota ikan, tetapi, juga merusak habitat ikan.
Degradasi Lingkungan dan Alat Pelestarian
Menurut Abdurrahman, akhir-akhir ini ikan semakin berkurang dan mangail (tangkap) ikan harus ke laut jauh bila ingin mendapat hasil maksimal. Ikan sudah menjauh, tidak seperti dulu dan mungkin akibat bunyi mesin kapal laut, banyaknya sampah dan kerusakan ekosistem.
Selain faktor yang disebutkan, juga terjadi perubahan cuaca tidak menentu. Dulu biasanya musim ikan pada bulan tertentu dan para nelayan punya pengetahuan itu. prediksi mereka tidak pernah meleset. Tetapi, sekarang musim ikan tidak menentu dan sulit diprediksi. Perubahan ini bisa jadi dampak dari perubahan cuaca yang tengah berlangsung.
Sore yang senja, di pesisir pantai desa Cobodoe, Tidore Kepulauan (Tikep) Haikal (67) menjelaskan pengalaman menangkap ikan gunakan salah satu alat tangkap tradisional yaitu panah. Panah adalah satu dari sekian alat tangkap yang hingga sekarang masih digunakan oleh nelayan. Penggunaan alat tangkap ini butuh keahlian khusus terutama soal mengatur pernapasan dan skil menembak.

Memanah ikan itu suatu pekerjaan yang tidak semua orang dapat melakukannya. Oleh karena di dalam air kita perlu mengatur nafas dengan baik, tenang dan fokus agar bidikan tepat sasaran. Karena ikan sangat sensitif terhadap kehadiran predator. Memanah ikan tidak sekedar penuhi kebutuhan, melainkan juga menjadi hiburan tersendiri dan dapat menambah pengetahuan tentang kondisi laut. Misalnya kerusakan habitat, laut kotor atau tidaknya dan populasi ikan meningkat atau menurun.
Ikan yang ditangkap pun berukuran besar dan kecil dibiarkan tumbuh besar. Menangkap ikan gunakan panah tidak menguntungkan secara ekonomi. Namun, yang paling terpenting adalah kita teguh pada pendirian bahwa salah satu sumber makanan yang tidak dapat terpisahkan dari orang pulau adalah ikan. Artinya bahwa, sumber daya ikan perlu dijaga agar tidak habis.
Menurutnya ibarat jasa dan roh yang menjadikan manusia bisa hidup. Begitulah hubungan orang pulau dan laut. Laut itu seperti jasad manusia. Sebab dari hasil laut orang pulau mendapatkan nutrisi, protein yang membuat tubuh dapat tumbuh dan berkembang. Tanpa itu roh manusia akan terpisah dari jasadnya. Pemahaman ini yang diajarkan orang tua kepada kami, katanya.
Saat ditanya bagaimana kondisi laut sekarang ini. Haikal menjelaskan, sekarang kondisi laut makin berubah jauh. Di tahun 2000 batu-batu besar, karang masih utuh dan ikan pun tak kalah banyaknya. Sekarang batu di dalam laut berkurang jauh, karang banyak mati dan ikan pun entah berpindah kemana.
Hal ini disebabkan banyak orang mengambil batu di laut untuk kebutuhan bangunan rumah dan termasuk proyek-proyek pemerintah. Selain itu, sampah pun berhamburan di dalam laut, dan air laut seperti ditutupi kabut. Bisa jadi ini adalah penyebab ikan berpindah di laut dalam, kata Haikal.
Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun Ternate, Dr. Djanib Ahmad menjelaskan, di Indonesia ada tiga kategori nelayan diantaranya tradisional, postradisional dan modern. Di Maluku Utara 70-80 persen adalah nelayan tradisional dan postradisional. Nelayan tradisional itu alat tangkapnya sederhana, pendapatan minim, akses pasarnya rendah, hasil tangkap sedikit dan mudah rusak.
Sedangkan postradisional itu, katanya, perubahan alat tangkap nelayan tradisional berupa perahu dayung ke perahu bermesin, akses pasar mulai dijangkau dan mulai memikirkan kualitas produk. Tetapi pendapatan mereka masih rendah dan kategori miskin. Berbeda dengan nelayan modern yang sudah terindustrialisasi lebih utamakan tenaga terampil, kualitas unggul dan maksimaslisasi keuntungan, katanya.
Djanib Ahmad menjelaskan, problem mendasar nelayan tradisional dan postradisional adalah minim kapasitas. Mereka belum paham cara penanganan ikan yang baik dan maksimalisasi keuntungan. Soalnya lagi adalah, tak ada keberpihakan kebijakan pemerintah akibatnya terjadi marginalisasi dan kemiskinan.
Kebijakan dimaksudkan adalah meningkatkan armada laut, alat tangkap, kapasitas pengelolaan ikan yang baik dan benar. Sehingga hasil tangkapan pun meningkat, kualitas unggul dan memiliki daya saing di pasaran. Kebijakan ini yang perlu ditingkatkan dan tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan.
Sekalipun nelayan tradisional kalah secara ekonomi, katanya, namun dari segi lingkungan, pola tangkap mereka lebih ramah lingkungan. Karena kearifan lokal masih dipegang kuat dan peralatan digunakan pun tidak merusak ekosistem laut. Beda halnya nelayan modern, jika permintaan perusahan tinggi mereka kerap gunakan alat peledak (pengeboman), penggunaan zat kimia dan alat tangkap raksasa.
Reklamasi dan masifnya pertambangan mengubah pesisir menjadi pelabuhan, pembuangan limba, sampah rumah tangga menimbulkan masalah lingkungan cukup serius. Yang tak kalah bahayanya lagi, adalah mikroplastik maupun nanoplastik yang berasal dari sampah rumah tangga dan bahan kosmetik. Plastik berukuran kecil di lautan ini akan dikonsumsi ikan dan bila kita konsumsi ikan-ikan tersebut, maka, berpengaruh pada gangguan kesehatan.
Selain itu, katanya, perubahan lingkungan laut juga penyebab rusaknya ekosistem mangrov, lamun dan terumbu karang. Tiga habitat ini diantara satunya hilang akan sangat berpengaruh pada biota laut. Hutan mangrov di Maluku Utara saat ini tersisa 41.000 sekian hektar dari 63.000 hektar. Soal-soal ini yang dapat meningkatkan migrasi ikan. Lebih jauhnya, perubahan tersebut akan berakibat buruk pada kehidupan nelayan: kemiskinan.
Sehingga menurut Djanib Ahmad, harus ada kebijakan untuk merawat lingkungan laut. Baik nelayan tradisional dan lebih khususnya nelayan modern perlu menerapkan pola penangkapan ramah lingkungan. Penting mengembangkan serta melegalkan alat tangkap tradisional dalam bentuk peraturan daeah (Perda) dan peraturan desa (Perdes) di semua desa pesisir. Tujuannya, agar ekosistem laut terlindungi dan terawat.
Maluku Utara ini agak unik dibandingkan daerah lain, katanya. Hampir semua desa-desa pesisir di Kabupaten/kota punya kearifan lokal. Kearifan itu digunakan masyarakat untuk memproteksi potensi perikanan dan kelautan. Sehingga penting kiranya kearifan lokal dijadikan alat untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut. Di sini teori ekosentrisme yang diperkenalkan Lynn White menjadi relevan.
Lynn White menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab moral, tidak hanya terbatas pada kehidupan organik saja, tetapi juga berlaku untuk seluruh aspek ekologis. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber daya alam, perhatian harus diberikan terhadap pelestarian lingkungan (Ayuningutami & Najicha, 2022).