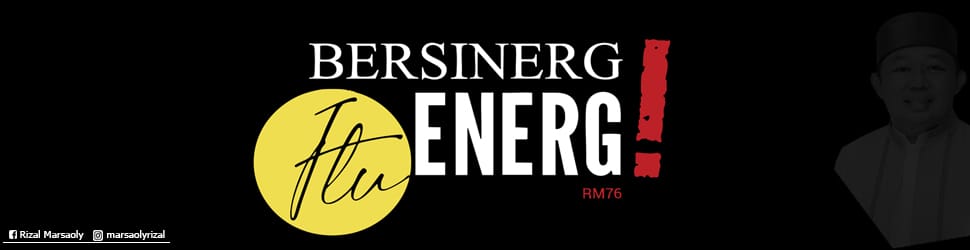Nurkholis Lamaau
(Jurnalis & Pegiat Lingkungan)
Memiliki cadangan nikel sebesar 3,5 miliar ton — sekitar 35 persen atau sepertiga dari total cadangan nasional — Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor hingga USD 1,2 miliar pada 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maluku Utara sendiri disesaki 127 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 655.581,43 hektare. Sebanyak 62 izin di antaranya merupakan izin untuk komoditas nikel dengan luas konsesi mencapai 239.737,35 hektare.
Tidak heran jika ekspor-impor tercatat surplus; kontributor ekspor seluruhnya merupakan komoditas non-migas dengan kontributor terbesar besi dan baja 60,11 persen serta nikel 34,68 persen.
Namun, di balik angka-angka gemilang itu, tersimpan sebuah paradoks: pertumbuhan ekonomi yang tinggi beriringan dengan angka kemiskinan yang kian mendalam.
Teluk Weda — kawasan industri yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi — justru menjadi kabupaten termiskin kedua di Maluku Utara.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,36 poin pada 2022 meningkat menjadi 1,80 poin pada 2023 — melampaui nilai rata-rata nasional sebesar 1,53 poin. Padahal, kawasan ini menyumbang Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tertinggi di Provinsi Maluku Utara.
Dimana, sektor industri pengolahan sebesar 33 persen serta pertambangan dan penggalian 19 persen menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketimpangan ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara belum sepenuhnya inklusif.
Pabrik-pabrik pengolahan ore menjadi nikel sebagai komponen baterai kendaraan listrik, tampak berdiri megah. Tapi warga sekitar masih bergulat dengan akses air bersih. Di kawasan industri Teluk Weda, IWIP membutuhkan pasokan air lebih banyak dari penduduk di seluruh Halmahera Tengah.
Pembesaran skala operasi IWIP mendorong ekstraksi air baku dari Sungai Sagea sebesar 15.000 m3 per hari, melampaui ekstraksi air yang terus berlangsung sebesar 12.000 m3 per hari dari Sungai Kobe, Sungai Sake, dan Sungai Woesna/Wosia. Perampasan air untuk melayani kebutuhan operasi IWIP dengan demikian berpotensi naik menjadi 27.000 m3 per hari.
Sebagai perbandingan, kebutuhan air untuk seluruh penduduk Halmahera Tengah yang berjumlah 96.977 jiwa pada 2023 adalah sebesar 10.667,47 m3 per hari, dengan angka konsumsi rata-rata 110 Liter per orang per hari.
Warga di Desa Sagea dan Desa Kiya sangat bergantung pada air Sungai Sagea. Sedangkan warga Desa Lukulamo, Desa Kulo Jaya, Desa Woejerana, dan Desa Woekob sangat bergantung pada air Sungai Kobe.
Namun, privatisasi pengelolaan Sungai Wosia dan Ake Sake oleh perusahaan membuat kedua sungai itu tidak lagi bisa diakses oleh warga Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf — dua desa yang berada dalam ring 1 kawasan industri.
Belum lagi pencemaran pada air Sungai Sagea, Ake Doma, Ake Sake, Sungai Kobe, hingga Sungai Woesna. Sebelum ada aktivitas pertambangan, sungai ini merupakan tipe sungai kelas I. Setelah adanya penambangan, indikasi pencemaran terlihat secara kasat mata. Air di sungai-sungai tersebut terlihat keruh berwarna kuning kemerah-merahan.
Khusus Sungai Kobe, Dinas Kesehatan setempat telah memperingatkan warga agar tidak menjadikan air dari Sungai Kobe sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti minum, memasak, mencuci.
Selain air bersih, lahan-lahan produktif warga juga kian menyusut. Sebagian besar lahan persawahan dan perkebunan di wilayah Transmigran Kobe meliputi Desa Kulo Jaya, Desa Woejerana, Desa Woekob, dan Desa Dowongi sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh petani.
Bahkan di Desa Woejerana, sejumlah petani menyulap lahan sawahnya menjadi tambak ikan. Tapi pada pertengahan Juli 2024, banjir besar yang melanda wilayah setempat membuat ikan-ikan jenis ikan mas dan nila, kabur dari kolam tambak.
Situasi itu sudah berlangsung sejak 5-6 tahun lalu. Penyebab petani tidak lagi menggarap sawah karena saat hujan deras, sungai Kobe meluap membawa material lumpur, yang mengakibatkan petani kerap gagal panen.
Tapi itu hanya satu di antara banyak faktor. Ada beragam pola perampasan lahan-lahan produktif warga yang secara umum terjadi di kawasan-kawasan industri. Dimana, perusahaan selalu menerobos lebih dahulu baru melakukan negosiasi. Siasat ini mempersempit pilihan warga: melepas atau bertahan.
Di saat yang sama, perusahaan mengklaim jika lahan-lahan warga yang diterobos paksa itu milik negara, meski warga telah menguasai puluhan tahun dan membayar pajak. Tidak sedikit warga diintimidasi dan diancam karena menolak menjual lahannya.
Pemilik lahan hanya diberi kompensasi tanpa menghitung tanaman yang tumbuh di atasnya. Warga yang bersedia menjual lahannya ke perusahaan mengaku tidak punya pilihan lain, selain melepas lahannya ke perusahaan.
Karena mereka sudah kehilangan akses terhadap lahan pertanian, di samping mendapat tekanan, ancaman, dan intimidasi dari aparat keamanan. Bahkan sebagian di antaranya memilih masuk hutan mengkaveling lahan untuk dijual ke perusahaan.
Praktik pengkavelingan itu kemudian mempermudah perusahaan dalam memproses pembebasan lahan demi kepentingan industri. Patokan harga lahan yang rendah juga menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Semua itu terlaksana atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sialnya, mayoritas korban dari industri kotor tersebut adalah masyarakat adat. Masyarakat adat yang saya maksud di sini adalah, tidak dalam bentuk atribut atau lembaga. Tapi seseorang yang terlahir, tumbuh, dan berkembang bersama tradisi yang mengikatnya sebagai manusia Halmahera.
Tidak mengherankan jika BPS pada 2023 mencatat, lahan perkebunan di wilayah Weda Tengah yang didominasi tanaman kelapa dan pala tersisa 143 hektare, dari sebelumnya seluas 523 hektare di 2013.
Untuk kawasan hutan hingga 2022 tersisa 181 hektare yang terdiri dari hutan lindung 33.000 hektare, suaka alam dan pelestarian alam 16.000 hektare, hutan produksi terbatas 63.000 hektare, hutan produksi tetap 25.000 hektare, dan hutan produksi yang dapat dikonversi 42.000 hektare.
Data Global Forest Watch mencatat, Halmahera Tengah telah kehilangan 27,9 kha tutupan pohon sejak 2001 dan emisi CO2 sebesar 22,4 Mt. Kini, wilayah tersebut telah kehilangan tutupan hutan seluas 823 hektare pada 2022.
Sementara, Halmahera Tengah dengan luas wilayah 227.683 hektare dibebani dengan berbagai aktivitas industri nikel. Terdapat 22 izin konsesi pertambangan nikel dengan total luas konsesi seluruh perusahaan mencapai 95.736,56 hektare atau sekitar 42 persen dari luas wilayah.
Padahal, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 didefinisikan secara gamblang, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, dijelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
Tapi dalam penetapan kawasan hutan di Maluku Utara, untuk kawasan hutan konservasi, dari total 218.990,98 hektare yang direncanakan, baru 215.398,65 hektare yang ditetapkan. Sementara itu, kawasan hutan lindung memiliki luas 559.536,27 hektare, namun yang telah ditetapkan hanya 434.864,39 hektare.
Ketimpangan juga terjadi pada kawasan hutan produksi. Hutan produksi terbatas memiliki luas 678.180,30 hektare, tetapi yang ditetapkan baru 376.998,24 hektare. Hutan produksi tetap seluas 482.947,16 hektare, dengan penetapan hanya 319.511,99 hektare. Adapun hutan produksi yang dapat dikonversi memiliki luas 539.321,98 hektare, namun yang ditetapkan hanya 365,19 hektare.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan hutan di Maluku Utara belum memiliki status hukum yang kuat sebagai kawasan hutan tetap. Ketimpangan penetapan ini berpotensi membuka ruang bagi ekspansi industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel, ke wilayah yang seharusnya dilindungi.
Di sisi lain, kawasan konservasi seperti Taman Nasional Aketajawe Lolobata, CM Pulau Obi, dan SM Goa Bokimoruru menghadapi tekanan dari ekspansi industri ekstraktif.
Direktorat Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, Maluku Utara telah mengalami defisit carbon stok dengan nilai emisi sebesar 0,147 Gigaton CO2 dan diproyeksikan menyentuh 0,399 Gigaton CO2 di tahun 2045, seiring dengan meningkatnya degradasi lahan dan deforestasi.
Pala, Kelapa, dan Harapan yang Tertatih
Di tengah tarik-menarik antara ekstraksi dan konservasi, antara pertumbuhan dan keadilan, Maluku Utara seakan berdiri di persimpangan sejarah. Apakah akan terus menjadi lumbung nikel yang memiskinkan, atau bertransformasi menjadi wilayah yang mengolah kekayaan alamnya dengan adil dan berkelanjutan.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD 2025 – 2029, pemerintah daerah mulai menyoroti potensi komoditas unggulan sebagai alternatif penggerak ekonomi. Pala dan kelapa menjadi dua komoditas utama yang menawarkan jalan keluar yang lebih berkelanjutan.
Berdasarkan analisis core competence wilayah, komoditas pala dan kelapa merupakan komoditas unggulan peringkat 1 dan 2 di Maluku Utara. Maluku Utara juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pala tertinggi ketiga nasional dengan produksi 6.083 ton dan luas tanam 68.778 hektare. Sementara kelapa menyumbang 200.000 ton produksi nasional, terbesar kelima, dengan luas tanam 204.000 hektare.
Berdasarkan kajian strategis rantai nilai wilayah regional III tahun 2024, kebutuhan investasi untuk industri pala bubuk sebesar Rp 42,7 miliar, minyak atsiri Rp 49,49 miliar, dan permen pala Rp 28,33 miliar. Namun, investasi untuk mengolahnya masih tertatih. Pilotplant pala bubuk, minyak atsiri, hingga permen pala baru sebatas kajian, belum menyentuh tanah.
Sementara, untuk potensi produksi pangan, subsektor perikanan dan tanaman pangan masing-masing berkontribusi sebesar 34,12 persen dan 8,80 persen terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB Maluku Utara (BPS 2025). Khusus pada produksi perikanan tangkap untuk ikan jenis tuna, cakalang, tongkol mencapai 85,153 ton yang kemudian menempatkan Maluku Utara di posisi kelima secara nasional (BPS 2025).
Dalam konteks ini, pembangunan Maluku Utara menghadapi dilema: antara melanjutkan ekspansi industri ekstraktif atau beralih ke model ekonomi berbasis komoditas lokal dan konservasi. Pilihan ini bukan sekadar soal angka. Tapi menyangkut masa depan ekologi, kesejahteraan, dan keadilan.